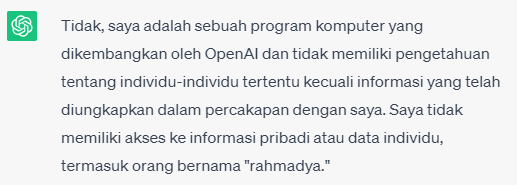“Kamu tahu beasiswa yang di atas 40 tahun?”, kata rekan saat santai ngobrol sambil menikmati kopi. Karena lama tidak baca berita tentang beasiswa, tentu saja saya kaget, ternyata Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mensyaratkan max 40 tahun. Dulu, di tahun 2013 ketika masih ditangani oleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN) maksimal berusia 47 tahun, yang beberapa bulan sebelumnya 50 tahun. Sementara yang dalam negeri (BPPDN) maksimal 50 tahun. Dari undang-undang MENPAN sih 42 tahun. Tapi yang jelas di atas 40 tahun masih boleh.
Beberapa rekan saya yang dari awal memang ‘super’ karena lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia (masuk 10 besar), bahkan ada yang dari luar negeri, entah mengapa sepertinya terlena untuk melaksanakan studi lanjut ke S3. Keasyikan menjabat merupakan faktor utama, disamping keasyikan lainnya. Padahal waktu itu mereka belum menikah, alias belum ada hambatan untuk belajar lagi.
Dihapusnya BPPLN memang merupakan bencana terbesar bagi mereka yang menunda studi lanjut, karena penggantinya, LPDP mengharuskan penerima beasiswa anak-anak muda. Memang kalau dilihat di kondisi real, kebijakan tersebut ada benarnya. Ketika saya berangkat, beberapa rekan ‘penghalang’ sebagian besar dosen-dosen senior yang lebih tua usianya. Namun ketika sampai di kampus tujuan dan mulai kuliah, saya seperti Pak RT .. alias paling tua. Untungnya perawakan Indonesia terlihat lebih muda dari usia sesungguhnya, dibanding rekan-rekan asia timur yang wajahnya ‘boros’ .. alias lebih muda dari wajah yang terlihat.
Apa boleh buat, sebagian lanjut dengan mengandalkan biaya sendiri yang kian tahun biayanya bertambah. Dalam waktu 5 tahun saja, biaya S3 di kampus swasta ternama di Jakarta, biayanya hampir naik dua kali lipat. Memang ada stok untuk beasiswa tapi ya itu tadi, maks 40 tahun. Termasuk rekan-rekan saya saya mulai kesulitan karena kampus hanya memberi beasiswa per fakultas satu/dua orang saja. Ditambah ketidakpercayaan akibat 1 orang DO dan satunya lagi meninggal karena COVID. Tentu saja pelajaran berharga bagi kita agar tidak menghalangi rekan kita yang diberi kesempatan untuk maju.
Studi lanjut dengan tanpa mempertimbangkan secara matang pun bisa berbahaya, salah satunya adalah linearitas. Ada satu prinsip dasar yang dijelaskan oleh rekan yang juga kakak kelas saya yang profesor. Beliau menggunakan prinsip susu kopi. Misalnya jika S2 komputer dan risetnya komputer, kita anggap komputer sebagai kopi. Maka untuk menjadi guru besar dia harus menjadikan kopi sebagai bahan utama, misalnya kopi panas, kopi lathe, atau kopi susu. Jika dia lanjut di bidang non-komputer, misalnya pendidikan, maka dengan S2 komputer dan S3 pendidikan, maka tidak bisa dikatakan kopi sebagai bahan utama, karena yang dilihat S3 maka masuk kategori susu kopi. Jika ingin jadi profesor, maka seluruh riset harus berbasis susu, bukan kopi. Padahal riset-riset sebelumnya adalah kopi (komputer). Yang jelas di akreditasi, jika prodi yang akan diakreditasi adalah jurusan kopi, maka yang dapat nilai hanya kopi murni atau kopi susu, sementara susu kopi tidak ada nilai di akreditasi. Tapi jika Anda hobi belajar dan tujuannya menuntut ilmu, itu tidak bisa disalahkan.
Sekali lagi, untuk dosen-dosen muda, mengingat ketertinggalan kita dengan negara lain yang jumlah doktoralnya lebih banyak, sebaiknya segera berangkat. Di sini kata berangkat berarti studi lanjut di luar negeri, karena ada hal-hal tertentu di luar pendidikan/ilmu yang dapat dibawa pulang untuk kemajuan bangsa. Atau kalau mau di dalam negeri pun ok. Sekian, semoga menginspirasi.

Bersama Pa John, pewawancara DIKTI, saat acara reuni penerima beasiswa DIKTI (sekarang DIKBUD)