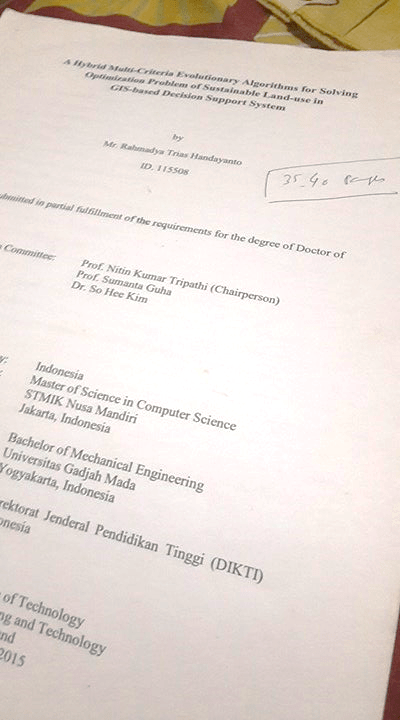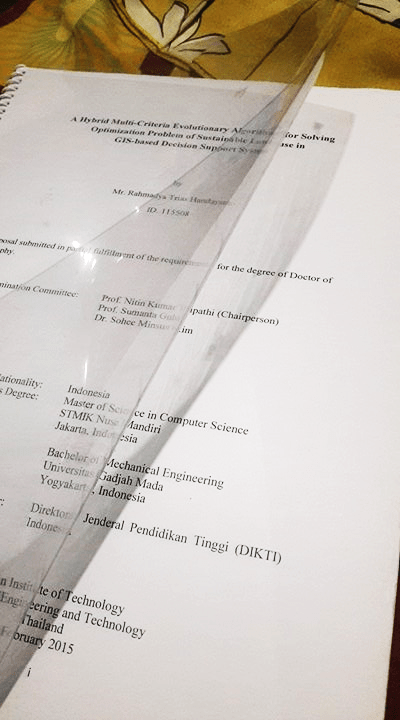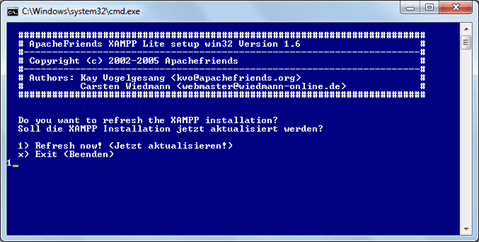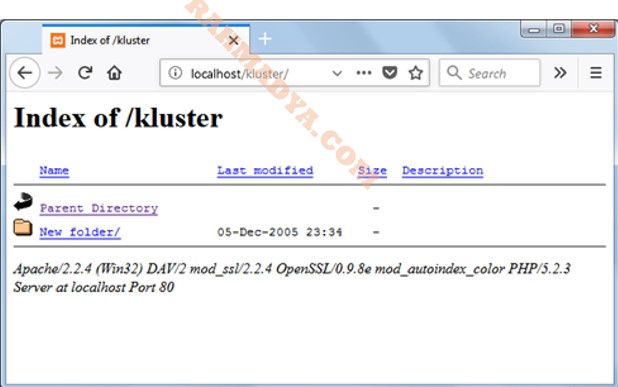Lihat di grup masjid kampus, cukup terenyuh oleh pamitnya rekan senior padahal belum selesai studinya. Teringat bantuan dan arahan yang dulu diberikan karena memang dia seorang Teaching Assistant (TA). Ketika saya telat datang, dia yang berkebangsaan negara di Asia Selatan, dengan suka rela memberikan satu CD berisi software ubuntu yang wajib digunakan dalam perkuliahan Web Programming (dengan ruby and rails). Setelah hampir sepuluh tahun kuliah doktoral, sepertinya dia harus pulang, entah alasan apa yang membuatnya tidak meneruskan kuliah, yang jelas saya dulu banyak dibantu olehnya.
Lengkap sudah saya kenal dengan rekan kuliah yang tidak selesai, pertama pulang karena alasan keluarga (tidak bisa ditinggal jauh), kedua meninggal, dan yang terakhir kelamaan kuliah. Dulu pun saya pernah mendengar cerita-cerita kegagalan mahasiswa doktoral, termasuk dosen saya waktu kuliah S1 dulu, tapi itu hanya dari mulut ke mulut. Berbeda dengan saat ini yang mengetahui langsung, bukan saja cerita tapi ikut merasakan kesulitan ketika bersamanya. Mungkin hal-hal berikut yang bisa “mengganggu” mahasiswa doktoral, bahkan menjadi penyebab kegagalan:
Syarat Course Work yang Berat
Tidak semua kampus mensyaratkan ikut kuliah dulu sebelum riset, tapi kebanyakan mensyaratkannya. Bahkan di Eropa ada gelar M.Phil. yang diberikan oleh mahasiswa doktoral yang tidak berhasil lolos ujian menjadi calon doktor (Ph.D.). Saya sendiri mengalami kesulitan karena memang background yang bukan dari jurusan sesungguhnya (multidisiplin). Repotnya terkadang kuliah digabung dengan mahasiswa master dan nilainya distribusi normal. Nilai bagus akan jadi buruk jika yang lain lebih bagus. Ditambah tugas project yang bareng dengan mahasiswa master yang kebanyakan malas karena bagi mereka c+ pun sudah lulus, dan hampir lulus semua. Sementara mahasiswa doktoral wajib minimal B+ atau total IPK = 3.5. Untungnya setelah mati-matian saya memperoleh 3.5 (A, A, B+, B, B, B+). Benar-benar mujur, pas, kalau tidak harus mengulang lagi dengan ancaman tidak dicover dari beasiswa jika melewati masa “jatah” beasiswa.
Ujian Kandidasi / Komprehensif
Setelah kuliah selesai, ada ujian yang menentukan berikutnya yaitu kandidasi, atau ujian menjadi calon doktor. Ketika awal kuliah sempat juga down, ternyata mahasiswa doktoral yang baru masuk statusnya adalah calon kandidat doktor. Jadi jangan sekali-sekali menyebut “calon doktor”, sering disingkat Dr.(c), kepada mahasiwa doktoral baru. Rekan saya yang di Taiwan lebih berat lagi, syarat kandidasi adalah 20 sks kuliah dan dua jurnal internasional diterima. Untungnya tidak ada syarat Impact Factor (IF), yang penting terindeks (biasanya Scopus). Untuk dalam negeri saya belum begitu mengerti, tapi proposal dibuat di tahun kedua, mungkin itu kandidasinya.
Tidak ada Progress
Walau tiap semester harus buat laporan kemajuan, tetapi biasanya terkesan formalitas, win-win solution antara pembimbing dengan mahasiswa. Tetapi repotnya tanpa progress sudah pasti kerjaan tidak selesai-selesai, karena kebanyakan pembimbing enggan menurunkan objektif sesuai yang dijanjikan proposal. Penyebab utama biasanya mahasiswa doktoral yang tidak “pure” kuliah, alias masih bekerja. Banyak rekan saya yang orang lokal (thailand) yang lama lulusnya karena mereka tidak 100% kuliah, alias sambil bekerja. Walaupun ada kebijakan kampus untuk mahasiswa tersebut (waktu D.O yang lebih lama) yang diistilahkan dengan “non-stay” student. Tetapi siapa juga mahasiswa yang ingin lulusnya lama?
Bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata kondisi lebih buruk lagi. Banyak rekan saya yang pindah kampus karena tidak selesai-selesai di kampus lamanya dengan berbagai alasan. Sempat saya menjadi asisten dosen waktu kuliah master di Indonesia dan bertemu dengan dosen doktoral UI. Saya menanyakan mengapa mahasiswanya lulus lama? Dengan santai dia menjawab, sebenarnya dia sudah menurunkan standar tetapi siswanya tetap sulit mengikuti, bahkan bertemu pun mereka jarang dengan alasan kesibukan bekerja. Ini saya alami sendiri ketika riset, kebanyakan memang saya di tanah air, tetapi jika dibandingkan sebulan di Indonesia itu kualitasnya sama dengan seminggu di Thailand karena memang di sana dari mata melek hingga merem (tidur) langsung mengerjakan disertasi. Paling nongkrong sambil ngopi di pinggir danau kampus dengan teman senasib.
Syarat Publikasi
Ini merupakan kendala utama yang tidak bisa diganggu gugat. Ini pula yang merupakan kontrol kualitas lulusan doktor suatu universitas. Tanpa publikasi, lulusannya masih diragukan kadar keilmuwannya. Rata-rata publikasi internasional menganut peer review dan author tidak bisa memaksakan agar tulisannya lolos. Sialnya di kampus saya mensyaratkan impact factor di atas atau sama dengan satu. Sulit dan lama untuk jurnal kategori tersebut (rata – rata masuk kategori Q2). Dengan syarat publikasi ini, pembimbing pun tidak bisa membantu kelulusan siswanya jika memang belum publish/accepted jurnalnya. Rekan saya yang bertahun-tahun belum publish pun ketika bertemu pembimbing, dia hanya bisa mendoakan saja. Gawat. Sebagai panduan untuk amannya suatu topic disertasi adalah: kesimbangan antara mudah dikerjakan dengan kemungkinan diterima di jurnal internasional ketika mengajukan proposal disertasi. Jika proposal mudah dikerjakan, biasanya sulit diterima di jurnal berimpact di atas satu, tetapi jika proposal sulit dikerjakan biasanya kemungkinan besar lolos di jurnal berimpact > 1 (paling kalau ditolak salah pilih domain jurnal atau masalah bahasa Inggris yang berantakan) tetapi bahayanya karena terlalu sulit jadi ga selesai-selesai.
Mungkin itu saja sedikit gambaran. Jika ingin lebih jelas, silahkan alami sendiri ya. Sebenarnya ada tahapan lain seperti pengecekan disertasi oleh external examiner (profesor dari luar kampus) dan sidang terbuka. Tetapi itu sepertinya hanya formalitas, biasanya dapat dilalui oleh mahasiswa doktoral. Sekian semoga postingan ini bermanfaat.

Tim Nongkrong (Ph.D., D.Eng, and D.Tech.Sc. Students)

Final Defense (Committees : Prof. Guha, Prof. Nitin, Dr. Kim)