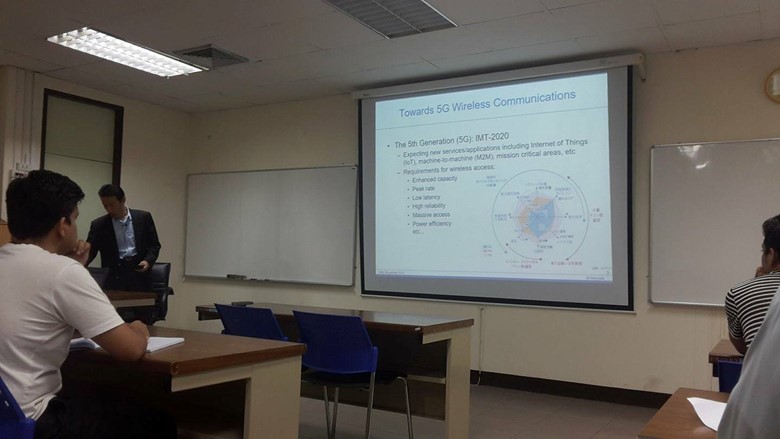“Ku mau tak seorang ‘kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu “. Penggalan puisi Chairil Anwar ini sejalan dengan ungkapan Frederich Nietzsche: Penderitaan membuat kita kuat. Tapi lebih simpel lagi mbah Marijan, cukup dua kata: “roso .. roso” hehe. Yuk, para dosen dan pengajar, tetap semangat, tetap kuat, hadapi saja.
Belakangan ini banyak sekali keluhan-keluhan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa yang mengeluh terhadap dosennya, terhadap institusinya, bahkan ada yang ingin meminta laporan keuangan kampus segala. Dosen yang mengeluh karena beratnya syarat-syarat naik pangkat, menerima tunjangan (lektor kepala dan guru besar), mengeluh karena Scopus, Sinta dan juga untuk memperoleh beasiswa (masalah kuota). Kampus yang mengeluh karena syarat Dikti berat, bahkan akreditasi C siswanya tambah dipersulit mencari pekerjaan. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Ristek-Dikti mengeluh karena kinerja dosen yang lemah dalam hal riset, tingkat pendidikan yang stagnan di master/magister, dan kasus-kasus yang menimpa kampus (bukan hanya swasta, melainkan juga kampus negeri). Salahkah keluhan tersebut? Tentu saja tidak, lalu bagaimana penyelesaiannya?
Posisi Negara kita Dalam Hal Pendidikan Tinggi
Sempat terbaca dalam share WA di handphone puisi dari seorang dosen yang merasa tidak nyaman dengan paksaan Ristek-Dikti terhadap Scopus yang dianggap kapitalisme dalam dunia pendidikan. Karena fokus ke riset, menurutnya, pengajaran ke mahasiswa jadi terbengkalai. Walau sepertinya agak cenderung ke “keguruan”, mungkin ada baiknya didengarkan. Keluhan-keluhan atau protes yang mempertanyakan sesuatu biasanya menggunakan logika yang masuk akal. Tetapi di dunia yang “fuzzy” ini, kata Zadeh: tidaklah ada sesuatu yang mutlak 100% tepat atau 100% tidak tepat. Bagi yang memprotes mungkin saja benar, tetapi tetap saja tidak 100% benar, kalaupun benar 100%, itu untuk variabel tertentu. Tidak tepat juga kita menurunkan level seseorang yang menginginkan sesuatu yang ideal. Misal pendapat: “seorang dosen harus memetenkan karya ilmiahnya”. Tentu saja kita tidak serta merta membantahnya, karena memang idealnya begitu, terutama dari jurusan teknik/rekayasa.
Akhirnya, sambil menunggu kabar siapa profesor external untuk menguji disertasi saya (biasanya dari Jepang), akhirnya saya menemukan beberapa buku di perpustakaan kampus. Salah satunya adalah “Revitalizing Higher Education” karangan Salmi. Buku ini cocok untuk kondisi negara berkembang seperti Indonesia.

Memang benar, karakteristik perguruan tinggi di negara berkembang harus dilihat dari sejarah dan kondisi perekonomian, juga politik. Ringkasnya, disimpulkan bahwa level perguruan tinggi di negara berkembang sebaiknya mengarah ke perekonomian dan industri untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju (dari sisi perekonomian utamanya). Fokus PT masih di level menciptakan tenaga-tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan bursa kerja. Agak berat juga jika dipaksa menciptakan paten-paten, walaupun banyak juga yang tercipta saat ini, misalnya telur bebas kolesterol dan produk-produk pangan dan obat lainnya. PT hanya bisa mengajarkan kewirausahaan tetapi tentu saja jiwa kewirausahaan tidak bisa dipaksakan. Yang jelas, bonus demografi di tahun 2020-an dimana angkatan kerja kita sangat tinggi harus diantisipasi. Tidak bisa hanya menganjurkan mereka berwirausaha, harus dipersiapkan skill khusus agar bisa bersaing (butuh sertifikasi internasional seperti perawat, las, CCNA, dan sejenisnya, bukan hanya skill berkendara utk jadi driver ojek online). Bahkan ahli-ahli las di dunia banyak dari negara kita (silahkan yang berminat, terutama las dalam laut). Jangan lupa ajarkan “Wisdom”, “Creativity”, dan lain-lain yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin/Artificial Intelligent ke anak-anak kita. Orang bijaksana dan kreatif biasanya ada saja cara untuk survive. Siapkan saja bekal, dan seperti kata Jack Ma: “jangan terlalu khawatir, tuhan pasti memberi karunia generasi masa depan potensi untuk bisa mengatasi problem-problem mereka di masa depan”. Sepertinya ada benarnya juga, percuma memaksakan suatu “jurus”, lingkungan mereka nanti berbeda dengan kita saat ini.
Posisi Pendidikan Tinggi di Negara Maju
Banyak yang protes bahwa publikasi di jurnal-jurnal internasional (atau juga seminar) cenderung mendukung sisi kapitalis mengingat pengelola jurnal atau pengindeks internasional menarik untung dari pihak-pihak yang ingin membaca atau mempublikasi artikel ilmiah. Ketemu juga buku yang membahas khusus masalah yang terkait hal tersebut yaitu “University Inc – Corporate corruption of Higher Education” karangan Washburn.

Buku ini membahas universitas-universitas terkemuka terutama di Amerika Serikat (big 5 atau bahkan big 10 ranking kampus dunia ada di sana). Amerika memang negara liberal dan kapitalis. PT di sana sudah maju dan jadi andalan perusahaan-perusahaan dalam hal riset. Ternyata, walaupun sudah maju, konflik muncul di sana. Beberapa perusahaan mengadakan kontrak dengan profesor (juga dengan bimbingannya yang biasanya mahasiswa doktoral) untuk riset perusahaannya. Kontraknya adalah untuk merahasiakan temuannya. Di situlah masalah muncul yakni peran PT yang tidak lagi independen (di negara kita lebih parah lagi, masih ada pengaruh politik, agama, dan lain-lainnya seperti almamater tertentu).
Sebenarnya peneliti yang mempublikasikan karyanya dia sedang mendermakan ilmunya untuk dipergunakan orang lain. Dan harus ada lembaga yang diakui untuk mempublikasikan karya ilmiah, yaitu pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal harus membayar ke penulis? Kalau dijawab “ya”, artinya ideal, seperti saya sebutkan di awal, seseorang yang memegang standar tinggi jangan kita paksa turunkan, biar saja karena itu bagus. Kenapa tidak kampus terkenal di dunia membuat jurnal dan membabaskan orang mengunduh dan mempublish karyanya? Mengapa harus perusahaan swasta? Baru baca beberapa halaman sudah tampak.
Beberapa universitas-universitas level atas bukan hanya profesor yang kerjasama dengan perusahaan, bahkan kampusnya pun bekerja sama, dengan kontrak-kontrak tertentu masalah kerahasiaan mengingat perusahaan itu sudah menggelontorkan “fulus” yang besar dan jangan sampai kompetitor ikut menikmatinya. Dan repotnya universitas-universitas itu kebanyakan disubsidi oleh pemerintah yang uangnya dari pembayar pajak. Repotnya di AS pembayar pajak memiliki kekuatan di dewan karena mereka perlu tahu uang itu lari ke arah yang sesuai, misal dalam hal pendidikan yaitu ke arah kemaslahatan bersama bukan menguntungkan perusahaan tertentu.
Ada suatu jawaban “trivial” masalah publikasi jurnal, silahkan pilih: (1) peneliti di PT boleh tidak mempublikasikan temuan dan memberikan hak pengelolaan ke perusahaan/merek dagang tertentu sehingga rakyat terpaksa membeli produk dan menguntungkan perusahaan dan peneliti tersebut atau (2) peneliti mempublikasikan temuannya yang bebas dimanfaatkan orang lain (atau perusahaan manapun) dan menguntungkan rakyat banyak, tetapi efeknya menguntungkan pula pengelola jurnal (misal grup Scopus). Kasus pertama yang heboh adalah penemuan vaksin polio oleh ilmuwan yang nekat mempublikasikan temuannya, walaupun tidak menguntungkannya, dari pada dimonopoli oleh perusahaan tertentu (akibatnya rakyat/negara banyak harus mengeluarkan dana ke perusahaan tersebut). Pasti ada yang menjawab dengan pilihan (3) peneliti bebas mempublikasikan temuannya tanpa kena biaya dan jurnal yang mempublikasikan membebaskan orang membaca tanpa harus membeli tulisannya. Kembali lagi, artinya ideal, seperti saya sebutkan di awal, seseorang yang memegang standar tinggi jangan kita paksa turunkan, biar saja karena itu bagus. Silahkan pilih pilihan (3) tapi jangan berharap banyak, apalagi memaksa.
Membuat Indeks Publikasi Ilmiah Sendiri
Mungkin level PT kita belum menyamai the big 10 universitas-universitas di Amerika Serikat, atau bahkan di Asia, atau bahkan lagi di Asia Tenggara. Evaluasi diri penting juga sih. Saat ini Ristek-Dikti mulai membangun Sinta, indek kinerja penelitian (dosen, dan jurnal Indonesia). Semoga tidak ada yang tidak setuju untuk kemandirian ini. Bolehlah tidak setuju Scopus dimasukan dalam variabelnya (karena katanya kapitalis). Boleh juga tidak setuju dengan Google Scholar dimasukan dalam variabelnya karena dikatakan abal-abal. Unik juga, yang ketat dan akuntabel tapi seperti Scopus ditolak karena kapitalis (profit oriented), yang tanpa biaya ditolak karena abal-abal. Balik lagi ujung-ujungnya ingin yang ideal. Seperti disebutkan di awal boleh jadi pendapatnya 100% tepat, tetapi tepat terhadap variabel tertentu saja. Untuk yang ideal dan memegang standar tinggi, jangan dipaksa menurunkan standarnya, biar saja kan bagus. Walau kalau tidak nurut ya repot sendiri juga.
Presiden kampus saya sempat mengeshare email dari presiden Harvard university akan keberatan biaya yang mahal untuk langganan jurnal (bisa dibayangkan sekelas Harvard saja mengeluh). Pertanyannya mengapa sekelas Harvard (atau gabung dengan top university lainnya) tidak bisa mengelola jurnal yang tanpa bayar? Atau satu negara, misal Amerika Serikat, Jepang, atau China, mengapa tidak bisa menciptakan indexer sekelas Scopus yang rapih dan akuntabel? Jujur saja saya dan mungkin pembaca juga sulit menjawabnya. Indonesia harus bisa dong .. Ya, saya setuju saja sih (kembali lagi ke idealis). Tetapi, sebagai gambaran, lihat gambar berikut ini yang diambil dari link jepang.
Bandingkan dengan negara kita dkk (gambar bagian bawah), tertinggal 8 kali dan 10 kali dengan AS dan China. Mungkin bisa untuk evaluasi diri (sialnya kok kalahnya dengan Malaysia). Mungkin kita tidak setuju Kapitalis, tetapi tidak mau menjadi Sosialis apalagi Komunis. Ya sudah, buktikan saja dengan mengalahkan China dan Amerika Serikat (grafik di bawah). Semoga tidak mengeluh lagi, tetap nekat berjuang seperti kata Chairil Anwar: “Ku mau tak seorang ‘kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu”.